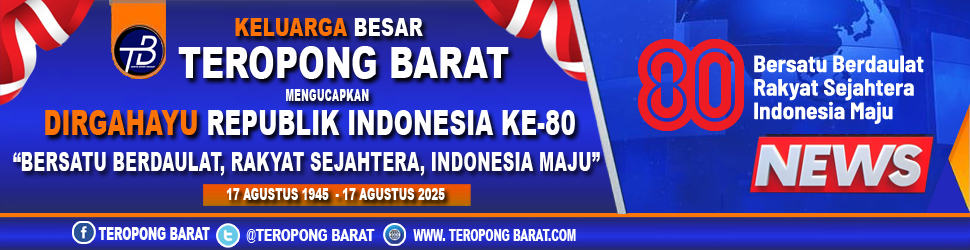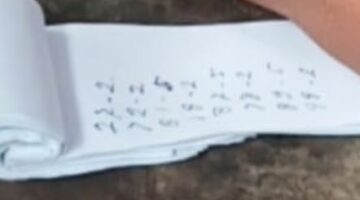Oleh Saridah(aktivitas muslimah)
Berikut ini tiga penyebab maraknya PHK para karyawan swasta di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Kebijakan PHK di Kota Balikpapan dianggap meningkat signifikan, dari berbagai sektor dari perhotelan hingga yang dominan adalah perusahaan minyak dan gas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan mencatat sebanyak 341 pekerja terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di awal tahun 2025.
Kebijakan yang Salah
Salah satu penyebab badai PHK yang kerap disorot publik adalah kebijakan impor pemerintah yang tidak berpihak pada industri lokal. Awalnya, Permendag 36/2023 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor mampu menekan arus masuknya produk luar. Peraturan yang resmi diterapkan pada 10 Maret 2024 itu membatasi masuknya berbagai produk impor ke Indonesia, sehingga dianggap menguntungkan industri lokal.
Sayang, usia aturan ini tidak lama. Kemendag kemudian menerbitkan revisi pertama aturan ini yaitu Permendag 3/2024 tentang perubahan atas Permendag 36/2023 pada April 2024. Selanjutnya terbit lagi Permendag 7/2024 hingga Permendag 8/2024. Bahkan banyak pihak yang sepakat mengenai perlunya revisi terhadap Permendag 8/2024. Pasalnya, regulasi ini berdampak pada menurunnya daya saing industri lokal, sedangkan pada saat yang sama negara juga memfasilitasi masuknya bahan baku serta barang jadi ke pasar domestik. Akibatnya, banjir produk impor di pasar domestik membuat kinerja industri yang padat karya menjadi lesu dan berimbas pada meningkatnya tren PHK.
Selain itu, ancaman PHK ini juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah lainnya seperti kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%. Hal ini membuat banyak perusahaan harus meminimalisir faktor produksi demi menyehatkan industri. Demikian pula dengan kebijakan kenaikan PPN dari 11% ke 12% turut menimbulkan efek karambol pada meningkatnya biaya produksi. Kondisi ini praktis menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menghemat biaya produksi. Walhasil, melakukan PHK pun menjadi pilihan.
Masalah Sistemis
Di tengah ancaman badai PHK, pemerintah masih optimis dengan kondisi ekonomi. Hal ini karena negara berpijak pada laporan neraca keuangan yang tercatat surplus. Pascarevisi pertama aturan Permendag 3/2024 tentang perubahan atas Permendag 36/2023 pada April 2024, Permendag 7/2024 hingga Permendag 8/2024, kinerja neraca perdagangan tercatat gemilang pada Maret 2024, dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) yang dirilis S&P Global sebesar 54,2 dan merupakan rekor tertinggi PMI manufaktur RI selama dua tahun terakhir. Sedangkan surplus neraca perdagangan terendah terjadi pada Juli yang besarnya USD0,47 miliar, dengan nilai ekspor capai USD22,21 miliar dan impor USD21,47 miliar. Juli 2024 merupakan bulan ketiga setelah Permendag 8/2024 resmi diberlakukan pada 17 Mei 2024. Hal inilah yang memicu protes banyak pihak terkait kebijakan impor pemerintah.
Secara umum, surplus perdagangan kerap menjadi patokan yang mengindikasikan sehatnya kondisi perdagangan satu negara. Dengan kata lain, barang-barang yang diproduksi oleh satu negara memiliki permintaan tinggi. Seharusnya kondisi ini berdampak pada terbukanya banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataan justru sebaliknya. Oleh karena itu, masalahnya bukan semata memastikan neraca perdagangan mengalami surplus melainkan langkah negara menghadapi ancaman PHK dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Laporan surplus neraca perdagangan tidak otomatis mengindikasikan sehatnya ekonomi satu negara. Terlebih lagi, pemerintah yang fokus menghitung nilai neraca perdagangan kerap luput menghubungkannya dengan kondisi riil di lapangan.
PHK bukanlah perkara sederhana. Sebabnya, hal ini akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran hingga rendahnya daya beli masyarakat. Tentu banyak dampak negatif atas hal ini seperti meningkatnya angka kemiskinan, banyaknya golongan menengah yang juga masuk dalam kategori masyarakat miskin, juga dampak ekonomi dan sosial lainnya.
Di sisi lain, salah satu penopang dalam sistem kapitalisme liberal yang diadopsi negeri ini adalah ekonomi nonriil seperti pasar saham, valas, maupun obligasi. Dalam sistem ini, pertumbuhan sektor nonriil ini menunjukkan perluasan fungsi uang yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai alat tukar menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan.
Negara-negara kapitalis mengembangkan sektor nonriil ini untuk berinvestasi secara tidak langsung, yaitu dengan membeli saham-saham di pasar modal. Meski pada dasarnya, nilai ekonomi nonriil, seperti transaksi di bursa saham, jauh lebih besar dibandingkan nilai transaksi barang dan jasa.
Walhasil, data-data statistik yang kerap dijadikan sebagai ukuran untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi sesuatu yang klise. Realitas ekonomi masyarakat yang kerap dianggap membaik sejatinya justru memburuk. Hal ini diperparah dengan watak pemimpin sekuler yang populis otoriter. Para pemimpin dalam sistem ini hanya menjalankan perannya sebagai regulator untuk memenuhi kepentingan oligarki dan abai dalam menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.
Liberalisasi ekonomi yang hari ini berjalan dalam kerangka sistem kapitalisme menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri. Negara seakan-akan lepas tangan dan cenderung mengambil peran minor dalam hal ini. Sedangkan dunia industri yang dikontrol swasta hampir dipastikan berorientasi pada profit dalam menjalankan bisnis. Ketika kondisi ekonomi tidak menguntungkan, dalih efisiensi berupa PHK dipandang sebagai langkah efektif untuk menghindari kerugian bisnis. Dalam kondisi inilah, ekonomi rakyat dipertaruhkan.
Dengan demikian, badai PHK sebagai problematik ketenagakerjaan tidak lepas dari konsepsi ekonomi yang bersifat sistemis yang diterapkan satu negara. Oleh karena itu, penting kiranya menghadirkan konsep ekonomi sebagai komparasi dari sistem ekonomi kapitalisme hari ini.
Konsep Islam
Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat sejumlah konsep yang mengatur masalah perdagangan maupun ketenagakerjaan secara khas. Kedua masalah ini termasuk dalam pembahasan ekonomi yang memerlukan peran negara untuk menyelesaikannya. Beberapa konsepsi ini antara lain, pertama adalah negara (Khilafah), memiliki wewenang penuh dalam mengelola perdagangan luar negeri. Negara diperbolehkan untuk melakukan impor sejumlah produk atau bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Kendati demikian, sebagai negara yang mandiri, Khilafah wajib berusaha untuk memberdayakan para ahli agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan dapat dihasilkan di dalam negeri.
Oleh karena itu, kebijakan impor yang diterapkan tentunya tidak boleh mengancam keberadaan industri lokal seperti yang terjadi saat ini. Negara hanya akan melakukan impor sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Apabila kebutuhan dalam negeri sudah dapat dipenuhi atau telah ada secara mandiri, negara bisa menghentikan impor tersebut.
Kedua, dalam sistem ekonomi Islam, ukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan di sektor riil. Pemerintah maupun swasta dilarang mengembangkan sektor nonriil. Peningkatan ekonomi dan bisnis dalam sistem ekonomi Islam fokus pada pengembangan sektor pertanian, perdagangan barang dan jasa (baik domestik maupun internasional), pengembangan sektor nonpertanian, serta kerja sama bisnis yang terbentuk dari berbagai syirkah atau kemitraan untuk membantu para investor yang tidak memiliki keahlian bisnis dengan para pengusaha yang memerlukan dana untuk memperluas usaha mereka.
Ketiga, memastikan terbukanya lapangan kerja. Problematik dunia kerja sesungguhnya berfokus pada usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Isu pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan dengan kebutuhan akan barang (seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal) serta layanan jasa (seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan). Dengan demikian, inti dari masalah ini terletak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Negara dapat memaksimalkan pemasukan melalui SDA yang terkategori sebagai kepemilikan umum dan dikelola secara mandiri oleh negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kepemilikan umum tersebut dalam hadis, “Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud). Dalam penuturan Anas ra., hadis tersebut ditambah dengan redaksi “wa tsamanuhu haram” (harganya haram). Artinya, dilarang untuk diperjualbelikan.
Dengan menjalankan perannya sebagai pengelola SDA secara mandiri, negara tentu akan memberikan peluang banyak lapangan kerja. Walhasil, negaralah yang memiliki peran utama dalam mengontrol ketersediaan lapangan kerja, bukan dunia industri (swasta).
SDA yang tidak bisa diakses secara langsung oleh semua orang—karena memerlukan keterampilan, teknologi canggih, dan dana yang besar—seperti minyak, gas, dan mineral lainnya dikelola sepenuhnya oleh negara. Negaralah yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengeksplorasi SDA tersebut. Semua hasil yang diperoleh disetorkan ke baitulmal. Khalifah memiliki hak untuk membagikan keuntungan dari SDA ini berdasarkan pertimbangannya demi kebaikan bersama.
Untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan secara menyeluruh, negara harus memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menstimulus daya beli masyarakat, negara harus mampu menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas khususnya bagi laki-laki sebagai qawwam dengan berbagai mekanisme. Hal ini bisa saja dengan membuka lapangan kerja di berbagai sektor, memberikan modal bisnis, iqtha’ (pemberian), dan lainnya. Seluruh mekanisme ini dijalankan untuk memastikan agar rakyat mampu memenuhi kebutuhan asasi mereka secara menyeluruh.
Dalam tataran teknis, negara tentu membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mewujudkan kemaslahatan umat sebagai implementasi dari tugasnya sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, negara mampu memberikan pelayanan maksimal dalam memenuhi kebutuhan rakyat, menggaji para pegawai negeri di setiap departemen melalui konsep APBN berbasis baitulmal, alih-alih menerapkan pajak yang mencekik ekonomi rakyat. Paradigma inilah yang menjadi pembeda antara konsep Islam dengan sistem lainnya seperti kapitalisme maupun sosialisme. Wallahualam bissawab.