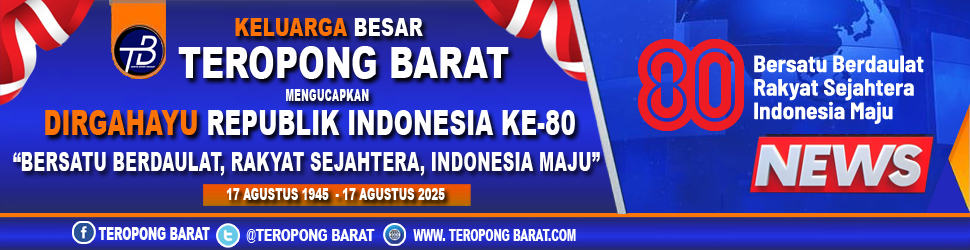Subulussalam, teropongbarat.co. Syair sahdu “Asai Nanggroe” dari seniman Rafly Kande mengalun seperti doa yang patah di tengah tanah yang kaya namun terluka. Lagu itu bukan sekadar nyanyian, melainkan ratapan halus atas bumi Aceh yang agung, tetapi tak sepenuhnya dimiliki oleh pewarisnya. Syair ini mengandung sindiran dalam kesyahduannya: Aceh yang penuh keindahan, tetapi masyarakat adatnya terpinggirkan di tanah sendiri.(24/06).

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di jantung kota Subulussalam—tanoh rencong Sheh Hamzah Fansuri yang mestinya menjadi tempat hidup yang adil bagi semua, termasuk masyarakat adat—justru menyimpan luka yang tak tampak. Hak-hak adat belum benar-benar hidup karena ketidaktahuan masyarakat sendiri, bahkan tokoh-tokohnya. Mereka tak menyadari bahwa tanah, hutan, dan budaya yang diwariskan leluhur adalah sumber kuasa dan martabat yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Kisah Pertaki Jontor di Kemukiman Penaggalan, kisah Kemukiman Binanga dan kemukiman Sambo deretan perustiwa memyakitkan bagi masyarakat adat.
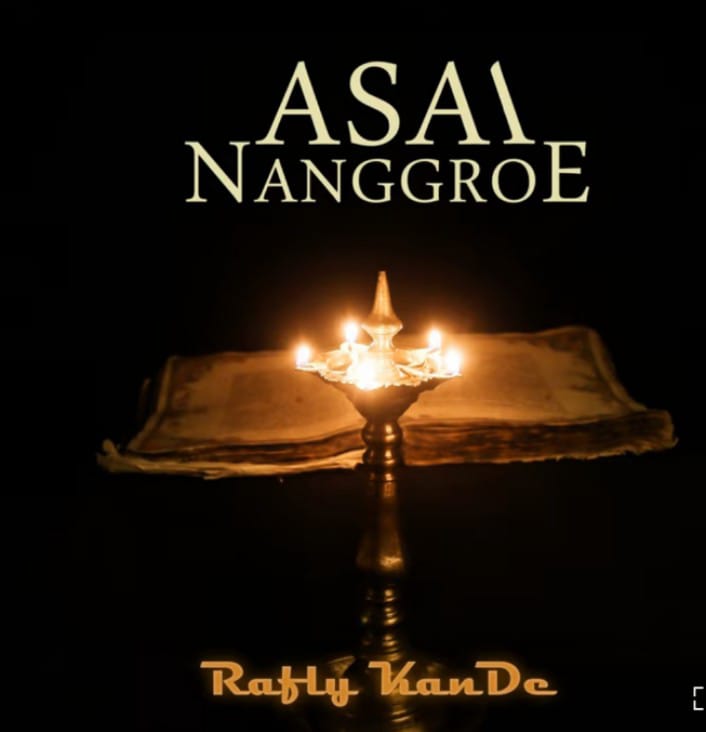
Padahal, sejak MoU Helsinki 2005, dunia telah mengakui kekhususan Aceh. Kemudian diperkuat lewat UUPA, qanun-qanun lokal, bahkan dukungan Mahkamah Konstitusi dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP 2007). Semua itu menjadi fondasi yuridis untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat: dari tanah ulayat, hutan adat, sampai hak atas pengelolaan sumber daya alam secara mandiri.

Namun di tengah legitimasi itu, masyarakat adat masih dikebiri oleh ketidaktahuan dan lemahnya pendidikan hukum adat. Institusi adat seperti Mukim, Imum Mukim, dan Tuha Peut hanya menjadi simbol yang kehilangan daya tawar. Tak sedikit seniman, budayawan, dan tokoh adat Aceh yang hidup dalam keterbatasan, jauh dari kesejahteraan yang semestinya mereka nikmati.

“Asai Nanggroe” bukan hanya puisi tentang keindahan tanah, ia adalah cermin pilu bahwa Aceh telah lama memeluk kekayaan tanpa bisa menikmatinya. Alam yang subur—hutan yang menjadi paru-paru dunia—tak bisa dinikmati oleh pemilik sahnya, karena hukum yang berpihak belum turun hingga ke akar rumput. Rafly Kande menyampaikan lewat nada: betapa damainya tanah ini, tapi betapa sunyinya suara orang-orang adat yang kehilangan haknya.
Kini saatnya kita bertanya: Apakah kita akan terus membiarkan masyarakat adat hidup menderita di atas tanah leluhurnya sendiri?
Ataukah sudah tiba waktunya untuk menyuarakan, mendidik, dan memperkuat posisi mereka, bukan sebagai simbol romantis masa lalu, melainkan sebagai pemegang masa depan Aceh yang berdaulat dalam adat dan martabat?
Penulis: Ketua LSM Suara Putra Aceh
Antoni Tinendung