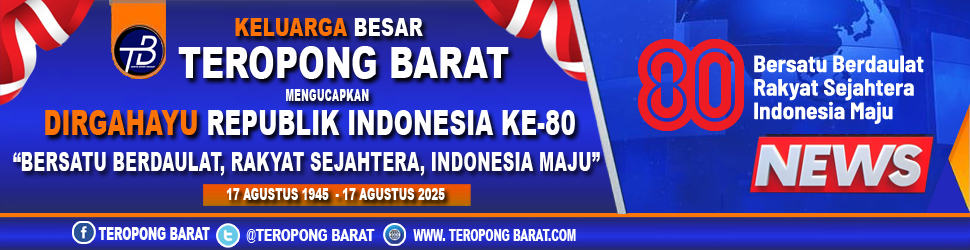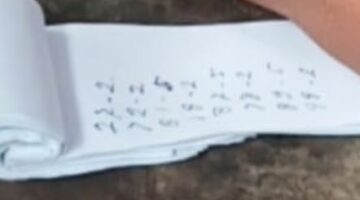Oponi-Teropongbarat.com||Belakangan ini, kasus perundungan atau bullying kembali marak dan menyita perhatian publik. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, berita tentang siswa atau mahasiswa yang menjadi korban kekerasan, ejekan, dan intimidasi terus bermunculan. Ironisnya, sebagian kasus baru terungkap setelah korban mengalami trauma mendalam, bahkan ada yang berujung pada kematian. Fenomena ini seharusnya menggugah kesadaran kita semua: ada yang salah dalam sistem pendidikan dan budaya sosial kita. Bullying bukan sekadar kenakalan anak sekolah. Ia adalah bentuk kekerasan yang lahir dari ketimpangan relasi, hilangnya empati, dan lemahnya penegakan nilai kemanusiaan di lingkungan pendidikan.
Sebagai seorang akademisi, saya melihat bahwa perundungan di ruang pendidikan merupakan potret buram kegagalan kita dalam mendidik dengan nurani. Sekolah dan kampus yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya karakter justru berubah menjadi ruang penuh tekanan dan ketakutan bagi sebagian anak muda. Dalam banyak kasus, bullying tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari budaya kekuasaan yang tidak sehat: senior merasa berhak mendominasi junior, yang populer merasa lebih berkuasa atas yang dianggap “tidak gaul”. Kekerasan yang seharusnya ditolak justru dianggap wajar dan “tradisi”. Kalimat seperti “dulu saya juga digituin kok” menjadi pembenaran yang terus diwariskan. Yang lebih menyedihkan, tidak sedikit lembaga pendidikan memilih menutup mata. Pihak sekolah, guru, atau bahkan dosen sering kali enggan menindak tegas dengan alasan menjaga nama baik institusi. Akibatnya, pelaku merasa kebal, sementara korban menanggung luka sendirian. Padahal, sikap diam adalah bentuk pembiaran. Saat kekerasan dibiarkan, kita sedang menciptakan generasi yang terbiasa menindas dan menormalisasi penderitaan orang lain. Nilai empati dan solidaritas perlahan terkikis dari ruang-ruang belajar yang seharusnya menumbuhkan karakter.
Dampak bullying tidak berhenti pada lebam di tubuh atau air mata di pipi. Luka paling dalam justru ada di hati dan pikiran korban. Banyak anak dan mahasiswa yang kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari pergaulan, hingga mengalami gangguan psikologis berat. Sebagai dosen, saya pernah melihat langsung bagaimana mahasiswa yang menjadi korban perundungan kehilangan semangat belajar dan menjauh dari lingkungan kampus. Mereka tidak hanya terluka secara emosional, tetapi juga merasa tidak punya ruang aman untuk bersuara. Jika lingkungan pendidikan gagal melindungi mereka, kepada siapa lagi mereka harus mengadu? Pertanyaan ini seharusnya cukup untuk membuat kita semua, terutama para pendidik dan pengambil kebijakan, merasa terpanggil.
Pemerintah tidak bisa lagi hanya bersikap reaktif setiap kali kasus bullying viral di media sosial. Penanganan yang tuntas membutuhkan kebijakan yang kuat, sistem yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Pertama, setiap satuan pendidikan harus diwajibkan memiliki unit perlindungan peserta didik yang benar-benar berfungsi. Unit ini perlu melibatkan guru, psikolog, dan konselor yang terlatih untuk menangani kasus bullying secara cepat dan profesional. Mekanisme pelaporan juga harus aman dan rahasia agar korban berani bersuara tanpa takut diintimidasi. Kedua, penegakan aturan tidak boleh tebang pilih. Jangan ada lagi kasus yang disembunyikan demi reputasi sekolah atau kampus. Pelaku harus ditindak dengan tegas, dan korban harus mendapatkan perlindungan penuh. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan bisa ikut memantau implementasi kebijakan anti-bullying di setiap wilayah. Ketiga, pendidikan karakter harus menjadi roh utama pembelajaran, bukan sekadar slogan di spanduk. Nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama harus dihidupkan dalam keseharian sekolah dan kampus. Guru dan dosen perlu diberi pelatihan khusus agar dapat mendeteksi dan mencegah perilaku kekerasan sejak dini. Dan keempat, pemerintah perlu membangun platform nasional pelaporan kekerasan di lingkungan pendidikan yang mudah diakses oleh siswa, mahasiswa, maupun orang tua. Sistem digital semacam ini bisa menjadi saluran pengaduan independen yang membantu menembus budaya diam di sekolah dan universitas.
Masalah bullying tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau pihak sekolah. Ini adalah tanggung jawab moral bersama. Orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Teman sebaya perlu diajarkan untuk berani membela, bukan ikut menertawakan korban. Media juga punya peran besar. Alih-alih memberitakan dengan nada sensasional, seharusnya media menjadi sarana edukasi publik tentang pentingnya pencegahan kekerasan dan empati sosial. Bagi kalangan akademisi dan dosen, tugas kita bukan hanya mengajar teori di ruang kelas, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan di setiap interaksi dengan mahasiswa. Kampus harus menjadi teladan budaya dialog, bukan arena kekuasaan yang menindas.
Bullying yang terus berulang adalah sinyal bahwa kita sedang kehilangan arah dalam mendidik generasi. Pendidikan bukan hanya soal nilai rapor dan gelar akademik, tetapi soal membentuk manusia yang mampu menghargai sesama. Jika sekolah dan kampus gagal menjadi ruang aman bagi anak-anak muda, maka kita sebenarnya sedang mencetak generasi yang pandai berpikir tapi miskin rasa. Dan di situlah letak kegagalan sejati dari sebuah bangsa yang mengaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT